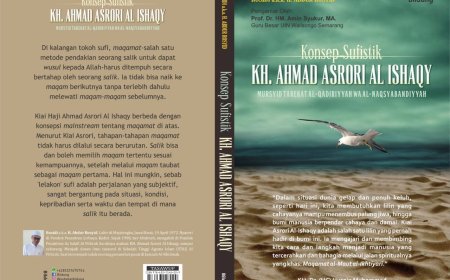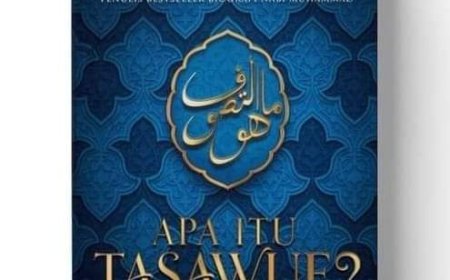KH. Hasyim Asy’ari, Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri (2)

KH. HASYIM ASY’ARI: GURU PARA KIAI PESANTREN DAN “WARANA” KEARIFAN NUSANTARA
Oleh Ahmad Baso
KH. Hasyim Asy’ari, Pesantren dan Kearifan Nusantara: Filosofi Santri Berguru
KH. Hasyim Asy’ari adalah sosok paripurna seorang “alim” yang selalu dikejar ilmu dan barakahnya oleh kalangan santri dan masyarakat. Hingga makamnya pun tidak pernah sepi dari para penziarah. Tidak heran kalau Tan Malaka sendiri selama hidupnya menyempatkan diri berguru pada beliau di pondoknya di Tebuireng dari maghrib hingga shubuh pada tanggal 12 atau 13 November 1945.9
Sebutan “alim” dalam masyarakat bangsa kita menunjukkan bahwa seorang guru, kiai atau ulama mengajarkan sikap-sikap beragama yang bukan sekedar teori, tapi juga contoh, amalan, dan suri tauladan. Sang kiai menjadi pembimbing para santri dalam segala hal, yang mendampingi para santri selama 24 jam sehari. Sehingga kaum santri menyaksikan sendiri di depan matanya contoh-contoh yang baik dari gurunya, yang kemudian secara langsung – tanpa instruksi atau paksaan – mengikuti sendiri amalan-amalan yang baik itu.
Lebih dari itu, amalan-amalan keagamaan juga dirasakan makin sempurna dengan mengikuti contoh ideal pelaksanaannya oleh sang kiai. Seperti halnya cara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadah shalat kepada para sahabatnya dengan “memperbanyak melihat cara Nabi melakukannya”. Demikian pula yang ditunjukkan oleh sang kiai dalam mengajarkan amalan-amalan keagamaan sehari-hari. Intinya, makin banyak melihat sang guru — artinya, berinteraksi secara rapat dengannya dan tidak menjauh – akan makin sempurna pelaksanaan ibadah tersebut. “Adat kelakoean sang goeroe di dalam hidoepnya sehari-hari jang penoeh dengan kedjoedjoeran dan kesoetjian itoe, mempengaroehi djuga atas sikap kehidoepan, levenshouding-nja, moerid-moeridnja”, demikian yang ditulis dokter Soetomo tentang pengajaran pesantren.
Jadi, kehidupan sehari-hari, amalan beserta sikap sang kiai lalu menjadi pedoman, dan bukan sekedar retorika. Sang kiai menjadi cermin dimana sang santri mengamati karakter idealnya. Dan watak “alim” adalah tipikal cerminan ideal tersebut. Dan karakter ke-alim-an yang paling tinggi di mata orang-orang pesantren adalah sikap ikhlas dan wara.
“Nderek kiai” atau “gurutta mato” adalah satu cara pesantren membentuk kepribadian kaum santri. Karena praktik latihan dan proses berguru itu tidak dilakukan dengan cara duduk di dalam kelas dengan jadwal-jadwal pasti.Pesantren dan proses berguru di sana merupakan sebuah proses bermasyarakat, satu cara menjalani kehidupan di dunia ini sebagai persiapan menuju ke gerbang akhirat. Seperti halnya menuntut ilmu itu sendiri tidak pernah berhenti, dari masa kecil hingga meninggal. Proses bermasyarakat dan menjalani hidup ini merupakan inti dari pemahaman keagamaan kalangan pesantren, yang mengamalkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah (disingkat Aswaja).
Hal itu berjalan dengan sendirinya, tanpa ada pengarahan dari sang guru. Guru tidakmemberitahuapa yang harus dikerjakan, tapi dia menegur kalau ada kesalahan. Kaum pesantren, bagaikan musisi jazz, saling berinteraksi dan kemudian membentuk satu kesatuan dalam proses tanpa ada pengarahan dan rencana sebelumnya. Semuanya dilakukan secara bersama dalam proses. Dan itulah arti bermasyarakat dalam ungkapan “nderek kiai” atau “gurutta mato”. Seperti halnya proses menuntut ilmu pada kiai-ulama tidak akan berhenti, bahkan untuk meminta bacaan dan aji-aji sekalipun, proses berkebudayaan dan bermasyarakat juga tidak akan pernah berhenti. Tradisi dan praktik kebudayaan mereka – dalam lingkup tradisi pesantren – lahir setiap hari, setiap kali dipentaskan dan dipanggungkan, dihadirkan, diinvensi. Segalanya menjadi baru dan aktual, karena secara spiritual ada usaha untuk melakukan adaptasi, aktualisasi, dan interpretasi. Dalam tradisi pesantren dikenal tiga unsur pokok basisnya yang melangengkan proses berguru dan bermasyarakat tersebut: desa, kitab kuning dan rumah kiai-mesjid-pondok. Singkatnya, filosofi “nderek kiai” atau “gurutta mato” menegaskan satu prinsip panutan hidup, yang sekaligus merupakan jiwa kebudayaan dan kemasyarakatan kaum pesantren.
Karakter berguru ini muncul misalnya dalam sosok Pangeran Diponegoro selama nyantri di Tegalrejo, Yogyakarta, di tahun 1790-an. Seperti yang ia tulis dalam Babad Dipanagara: “Untuk meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, kami kerapkali pergi ke Pasar Gede [kini Kota Gede], Imogiri (Jimatan), Guwa Langse dan Selarong. Apabila ke Pasar Gede dan Imogiri, kami biasa berjalan kaki. Tetapi apabila ke Guwa Langse dan Selarong, kami naik kuda dengan banyak pengiring.
Di kedua tempat terakhir ini, kami sering menolong petani menuai atau menanam padi. Memang semestinya para pembesar menyenangkan hati rakyat kecil”.10
Jadi, berguru atau “nderek kiai” harus memastikan tercapainya pendidikan karakter yang ideal di mata kalangan santri dan mustami-nya. Di sana tradisi digerakkan, diamalkan, hingga ditampilkan di depan khalayaknya. Apa yang membuatnya bisa bertahan dalam relasi santri-guru ini, kalau tidak karena kehendak kaum santri untuk mengenal seluk-beluk kehidupan, kondisi masyarakat, serta arah dan tantangan perjalanan peradaban. Dalam proses berguru itu mereka bisa jadi melihatnya secara lain, serta menjawab tantangan dengan cara lain pula. Tapi yang penting adalah kekayaan khazanah pengetahuan dan sensitifitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Selain berargumentasi, melakukan diskusi, macapatan, sama’an, munaqasyah, berbahsul masail, musawaratan, atau semacamnya, mereka juga melakukan meditasi dan bicara tanpa kata-kata dalam proses berguru itu.
Mengapa meditasi dan bicara tanpa kata-kata? Di satu sisi berguru adalah proses bermasyarakat. Namun pada sisi lain berguru adalah juga proses berefleksi ke dalam, mengucilkan diri dari masyarakat umum, menanamkan kepekaan akan hakekat diri dan kepribadian, dan untuk menjaga nilai-nilai dan moralitasnya. Jadi itu sebabnya, selain pesantren ada di kota, dekat alun-alun dan bahkan di sekitar pusat-pusat kekuasaan, seperti di kraton atau pendopo mesjid jami (mesjid agung), pesantren juga hadir di pedalaman, di pedesaan.
Dalam proses bermeditasi dan mengasingkan diri itu, pesantren merengkuh hakikat otonomi kebudayaannya (istiqlal tsaqafi). Karena kebanyakan pesantren secara ekonomi mandiri, maka kesadaran kuat akan otonomi kultural selama berguru dan bermeditasi bisa dicapai. Selama proses itu sang santri – biasanya santri-santri senior atau partisipan dari masyarakat yang memang punya maksud demikian – menjalani proses pengekangan segenap hawa nafsu, disiplin diri hingga kerja keras mengayuh kaki dan tangan. Dalam proses itulah lahir sikap-sikap keutamaan yang menjadi ciri khas moralitas individual dan sosial pesantren: kesederhanaan, kerjasama, solidaritas dan keikhlasan.11 Moralitas inilah yang dipupuk secara terus-menerus dalam lakon “nderek kiai” atau “jejer pandito” – sehingga masyarakat Nusantara menyebut kebaktian kepada guru menyamai kebaktian kita kepada orang tua dan mertua, bahkan kepada Allah.
Dengan kata lain, berguru mengharuskan sang santri bukan hanya total kepada sang kiai, tapi juga mengerahkan segenap raga dan jiwa yang dimilikinya. “al-Ilmu la yu’thika ba’dlahu hatta tu’thiyahu kullaka” (Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya, sebelum engkau menyerahkan segenap totalitas dirimu kepadanya)”, demikian yang dikatakan Ibnu Jama’ah dalam bukunya, Tadzkiratu-s-Sami’ wa-l-Mutakallim fi Adabi-l-Alim wal-Muta’allim, yang merupakan salah satu kitab favorit KH. Hasyim Asy’ari sendiri.
Nyantri dan berguru berarti mobilisasi segala sesuatu yang bisa dinikmati dengan panca indera, lahir dan batin. Tidak ada batasan umur, asal-usul sosial, genealogi maupun bahasa. Nyantri bukan hanya proses belajar-mengajar, tapi sesuatu yang mengincar jiwa kaum santri. Ini seperti yang ditekankan Dokter Soetomo, “Kekoeatan batin haroes dididik; ketjerdasan roh diperhatikan dengan sesoenggoeh-soenggoehnja, sehingga pengetahoean jang diterima olehnja itoe akan dapat dipergoenakan dan disediakan oentoek melajani keperloean oemoem teroetamanja”.
Tradisi nyantri hanya memerlukan jiwa yang aktif, sementara yang lainnya menjadi tenaga pendukung. Pengembaraan spiritual itulah yang diperlukan seorang guru-kiai-ulama, yang menggelar pendidikan dalam sebuah komunitas. Di tangan sang guru, pengembaraan dan pendalaman itu tidak menjadi perintah-perintah yang pasti. Tapi semacam isyarat-isyarat yang memancing para santri dan masyarakat pendukungnya (mustami) memasuki suatu suasana mencipta dari sesuatu yang tidak pernah jelas, sebelum benar-benar terjadi. Improvisasi dan kreatifitas merupakan institusi yang amat penting dalam tradisi pesantren. Karena ia merupakan tempat untuk mengaplikasikan segenap moralitas dan idealitas pesantren sedalam-dalamnya. Sehingga suasana pendidikan menjadi aktual.
Berguru, “nderek kiai” atau “gurutta mato”, dengan demikian, adalah sebuah usaha untuk hidup bersama tradisi. Bukan mengartikan tradisi sebagai mumi atau fosil yang mati, tapi sesuatu yang hidup, tumbuh dan menjadi bagian dari masa kini.Maka, dalam konteks nyantri ini, sang guru hadir seperti halnya sang sutradara. Di dalam sebuah kelompok yang akan menonton sesuatu sebagai sebuah pertunjukan, sutradara adalah seorang pencipta. Dia menciptakan dirinya lewat pemain dan segala sesuatu yang nampak dalam tontonan. Dan tontonan yang kemudian dinikmati oleh penonton adalah ciptaan dari berbagai
pribadi pemain, namun pada akhirnya adalah suara jiwa langsung dari sang sutradara, sang ideolog yang memainkan peran – dan itu adalah kiai-ulama. Seperti inilah lakon yang dimainkan sang kiai sebagai ideolog, yang menggerakkan tradisi, sekaligus mentradisikan gerakan. Masing-masing santri dan komunitas pesantren menjalankan peranannya, tapi ruh dari lakonan itu adalah tetap berasal dari sang guru.
Di dalam praktik berguru atau nyantri, sang kiai membuat dan melatih santri dan mustami-nya menjadi “pemain”. Pemain yang tidak terlatih sebagai pemain di atas panggung seringkali amat sulit untuk berpartisipasi dalam tontonan yang memiliki jiwa berbeda dengan pertunjukan. Setelah siap sebagai pemain, sang kiai sebagai guru memberikan perintah agar membawasebuah misi(seperti yang dilakonkan oleh Pangeran Diponegoro yang dibawa dari para kiai dan guru-gurunya dalam Perang Jawa 1825-1830) untuk disampaikan kepada masyarakat, komunitas lebih luas, kepada khalayak (mukhathab alaih), stakeholders, kepada penonton. Dalam pertunjukan/tontonan, para pemain bekerjasama seperti sepasukan prajurit dalam perang atau seperti pemain-pemain sepakbola melakukan total football untuk menciptakan tontonan yang betul-betul dikendalikan oleh sebuah misi.
Sang kiai sebagai guru dalam pengertian ini tidak mengajarkan kaidah-kaidah umum tentang pertunjukan atau seni akting. Dia mengajarkan satu bahasa khusus yang paling diperlukan untuk lakon (mulai dari bahasa ke-Aswajaan, kemasyarakatan, kebangsaan (wathaniyah–jumhuriyah), Ratu Adil, komunisme-nasionalisme, anti-kolonialisme, dst) yang dipilihnya. Baru kalau kaidah-kaidah umum itu diperlukan, maka akan diajarkan.Tapi tidak untuk dipegang sebagai patokan abadi, hanya sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan bukan merupakan tujuan, tapi usaha untuk mengamankan misi tadi yang hendak disampaikan oleh sang aktor agar sampai kepada masyarakat atau khalayaknya.
Ini adalah sebuah bahasa pendidikan. Sebuah idiom dalam tradisi pesantren. Bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah kerajaan teater dengan ideologi spiritual dan keyakinan- keyakinannya yang tersendiri. Sehingga sulit untuk dianggap akan memproduksi pemain-pemain yang bisa dipakai oleh kelompok yang lain (misalnya yang akan dipakai untuk mendukung tujuan- tujuan kolonialisme atau yang anti-kebangsaan) kecuali dengan pihak-pihak yang memiliki garis ideologis yang sama.
Filosofi dasar dari konstruk sang sutradara-kiai-ulama ini adalah bertolak dari Yang Ada. Dasar pikiran ini, yang juga merupakan ideologi spiritual mereka (ingat moralitas qana’ah), adalah upaya menerima apa yang ada di tangan dan di sekitar. Lalu mereka melakukan optimalisasi dari apa yang ada tersebut, untuk mencapai apa yang mereka targetkan. Baik seluruh peralatan, semua kebutuhan, tempat bermain, cerita, pemain-pemain pendukung, dan sebagainya, dimanfaatkan dari apa yang ada ini. Tidak berarti dengan menerima apa yang ada, mereka menjadi terbatas. Justru dengan mengerti keterbatasan mereka yang nyata, mereka kemudian memperoleh peluang untuk melakukan atau mendapatkan apa yang harus ada. Itu yang mereka sebut “kreatifitas” (al-akhdzu). Dalam proses berguru itu, dengan modal kreatifitas, hampir tidak ada yang tidak mungkin.
Mencipta dan berkarya menjadi pekerjaan yang rutin. Karena dalam praktik, hidup di negeri yang serba kurang dalam berbagai sarana dan fasilitas, orang-orang pesantren kerja keras, memeras otak, mengerahkan segenap potensi, serta menaklukkan hampir segala-galanya dengan kreatifitas. Kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan mampu hidup dan bertahan. Berproduksi menjadi semacam proses berjuang,
karena menciptakan dan menjaga tradisi kepesantrenan, tradisi keulamaan dan kebangsaan, berarti menciptakan sesuatu dari apa yang ada ini. Untuk tidak menjadi seadanya harus dilakukan akrobatik pemikiran dan interpretasi yang kadangkala bisa berarti penukaran sudut pandangan serta penjungkirbalikan nilai-nilai yang dimapankan masyarakat. Inilah filosofis pesantren yang sangat khas dan kuat getarannya: qana’ah, sekaligusber-amal shalih, dan, setelah itu, tawakkal.
Memimpin, mengasah dan mendidik santri bagi sang kiai dalam keadaan kesederhanaan semacam itu, lebih merupakan usaha perang gerilya. Yakni, usaha menaklukkan segala keterbatasan. Usaha yang tidak terbatas kepada penciptaan setting, laku, lakon, formula hingga gerakan. Tapi sudah meluas menjadi usaha menciptakan konsep-konsep dan formula baru dalam menilai tradisi kepesantrenan. Sebuah meditasi, sebuah praktik syuyukhiyah (berguru) yang bermakna pengaturan strategi. Karena aspek-aspek tindakannya adalah darurat dalam kondisi keterbatasan itu (terutama di masa- masa puncak penjajahan Belanda di Jawa), maka diperlukan kiat-kiat, akal serta sudut memandang yang baru. Karenanya hasilnya juga berbeda dengan hasil-hasil produksi bertradisidan berkebudayaan lainnya dalam keadaan normal, yang tak jarang ada distorsi. Ada kelainan, penyimpangan-penyimpangan bahkan pemutarbalikan yang kemudian secara fantastis berubah menjadi sebuah orisinalitas, keunikan dan juga gebrakan! Contoh dekat tentang ini bisa dilihat dari konstruksi pesantren tentang Ratu Adil, komunisme dan nasionalisme.
Bisa dikatakan kemudian bahwa orang-orang pesantren mengajak orang memikirkan kembali, memikirkan sekali lagi segala sesuatu yang sudah pernah disimpulkannya atau yang sudah diterima sebagai kesimpulan. Bukan untuk mengajak
orang berbalik langkah atau mengingkari diri, tapi untuk mengaktualisasikan segala keyakinan-keyakinannya setiap saat. Dalam konteks itu, sang kiai hadir sebagai seorang pemimpin, sang pengatur strategi. Dalam mengatur strategi bukan hanya diperlukan akal tapi juga insting. Dan dari sana dihimpunlah beragam strategi dan kiat-kiat: strategi bahasa,strategi ruang,strategi visual, strategi psikologi,dan juga strategi manajemen. Bahkan kalau perlu strategi menyerang — semuanya sangat dituntut. Dari olah kejiwaan hingga fisik semua diasah. Dan ini menjelaskan mengapa anak-anak pesantren diajarkan olah bela diri hingga pematangan ilmu-ilmu kanuragan atau kedotan.12
Dalam tradisi pesantren, seorang kiai adalah seorang jenderal perang yang memiliki kekuasaan sangat besar dan tak terbantah. Tidak semua orang mampu dan bisa menjadi kiai yang adalah juga jenderal. Yang banyak adalah kiai yang hanya menjadi palaksana (eksekutif atau tanfidziyah) dari titah sang kiai-ulama-jenderal-ideolog (syuriyah). Hanya seorang pemimpin spiritual, seorang yang memiliki kemampuan jenderal perang, yang mahir dalam segala taktik berperang yang bisa menjadi seorang kiai di atas panggungkebudayaan, beragama, peradaban dan juga berpolitik.
Seorang kiai adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan teladan atau uswah dalam diri masyarakatnya, yang memberikan pengalaman spiritual. Bukan hanya menciptakan adegan-adegan atau lakon-lakon bagus dan bermoral di atas panggung kepesantrenan. Karena nyantri bukan hanya sebuah prose belajar-mengajar,pesantren bukan hanya pendidikan biasa seperti yang banyak dipahami secara keliru. Tapi juga sebuah peristiwa spiritual, sebuah upaya untuk mencari jatidiri manusia, untuk menjadi manusia yang paripurna (insan kamil). “Agar santri tidak memahami ‘kelas bersama Gus Dur’ sebatas kelas akademik, tapi lebih dari itu sebagai ajang pembentukan kemanusiaan yang ideal menurut Islam”, ujar seorang kiai di Ciganjur, Jakarta, sahabat akrab Gus Dur.
Bukan sekedar hubungan kerja, hubungan pengetahuan, berguru juga relasi pengabdian antar sesama. Ia merupakan kesempatan untuk nyantrik (mengikuti dan meneladani sang guru), untuk menemukan diri, dan juga kesempatan untuk berderma-bakti kepada guru dan komunitas. Berguru adalah sebuah pendidikan jiwa bagi para santri, untuk mengasah kepekaaan, memperhalus budi-pekerti (akhlaqul karimah), dalam berperilaku dan berpengetahuan, dan dalam bersikap terhadap berbagai aspek kehidupan. Pesantren dalam pengertian ini adalah sebuah padepokan. Untuk melakukan pemantapan- pemantapan sikap dan kepribadian, sehingga akhirnya mampu menyampaikan suara, posisi, sikap atau pendirian – untuk berbagai fenomena sosial-politik bahkan juga spiritual.
Ini bisa dibandingkan dengan hakikat dan karakter teater modern sebagaimana yang dipanggungkan dan dipraktikkan oleh Putu Wijaya. Budayawan asal Bali ini menyebut teater sebagai padepokan, sebagai kesempatan untuk mempelajari banyak hal dari seorang sutradara yang bertindak sebagai guru spiritual. “Teater bukan sekedar hubungan kerja, tapi pengabdian. Teater adalah sebuah kesempatan untuk nyantrik, untuk menemukan diri. … pendidikan jiwa terhadap para anggotanya, yang mengajarkan seni akting dan vokal, tapi perilaku dan sikap, terhadap berbagai aspek kehidupan. Teater bukan lagi sekadar pertunjukan hiburan, dengan kreasi artistik. Teater adalah sebuah komunitas spiritual”.13
Dan, pesantren, ternyata, melebihi dugaan Putu Wijaya sendiri; ia adalah panggung dahsyat dari seni memainkan berbagai lakon, akting dan vokal itu untuk kejayaan negeri ini. Itulah yang ditunjukkan KH. Hasyim Asy’ari bagi bangsa kita.[]
8 Lihat Ibid., bab 7.
9 Lihat dalam Harry A. Poeze, Verguisd en Vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949 (Leiden: KITLV, 2007), vol. 1, hal. 145-6.
10 Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka & Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), vol. 4, edisi 2, hal. 169.
11 Soal ini misalnya digarisbawahi oleh Ben Anderson dalam bukunya, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (Jakarta & Singapore: Equinox Publishing, 2006 [1972]), hal. 5-6, ketika menulis tentang revolusi di Jawa dimana aktor-aktornya adalah para pemuda yang kebanyakan dikader di pesantren.
12 Contoh ilustratif di sini adalah cerita awal berdirinya Pesantren Tebuireng, Jombang, di tangan KH. Hasyim Asy’ari. Karena gangguan keamanan dari para penjahat yang sewaktu-waktu bisa membahayakan orang-orang pesantren, Hadlratusysyekh mengambil inisiatif agar para santri bisa belajar ilmu silat. Untuk itu beliau mengutus seorang santrinya ke Cirebon meminta bantuan kiai-kiai terkenal di sana, Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Pangurangan, Kiai Syamsuri Wanantara, Kiai Abdul Jamil Buntet dan Kiai Saleh Benda Kerep. Kelima kiai jago silat atau pendekar itu datang ke Tebuireng mengajarkan para santri ilmu silat. Delapan bulan kemudian, para santri sudah menguasai ilmu tersebut, dan menjadi bekal mereka untuk menghadapi para bandit. Belakangan para bandit ini bertobat dan berguru kepada sang kiai ideolog ini dan menjadi mustami pesantren.
Juga diceritakan bagaimana KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU, menghadapi masyarakat yang suka main judi. Beliau jelas tidak menggunakan cara kekerasan memberantas perjudian. Tapi beliau menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk mengajak masyarakat ke jalan yang benar secara perlahan dan sabar: beliau ikut main kartu bersama mereka, lalu bisa mengalahkan para preman pelaku judi, hingga mereka bertekuk-lutut dan mau menjadi santri dan berguru pada pendiri Pesantren Tebuireng ini. Praktik-praktik perjudian pun dengan sendirinya ditinggalkan oleh masyarakat.
Lihat Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Solo: Jatayu, 1986), hal. 6-7.
13 Lihat Putu Wijaya, Bor: Esai-esai Budaya (Yogyakarta: Bentang, 1999), hal. 297-dst.